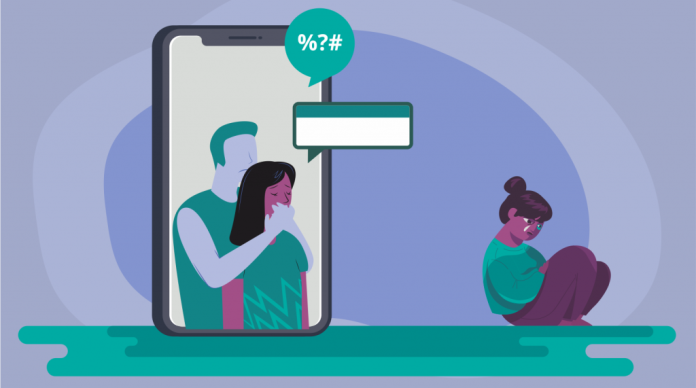“Saya trauma, tidak mau buka facebook lagi.”
Dunia maya saat ini menjadi ruang tanpa dibatasi waktu dan biaya. Dunia maya juga mudah dijangkau tanpa batasan usia. Penggunanya dari usia 17 ke atas dan kurang dari itu.
Ada hal yang positif tapi juga negatif. Secara positif, dunia maya membantu kita untuk mendapat informasi dan pengetahuan mengenai apa saja. Namun, sisi negatifnya juga tidak sedikit. Kecanggihan teknologi membuat kita dengan mudah mengetahui kejadian yang terjadi di sekitar kita maupun di dunia mana saja. Selain itu, teknologi internet juga berpotensi menjadi perpanjangan tangan untuk tindakan kekerasan. Salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang sering kali menyasar perempuan dan kelompok gender lainnya. Seperti cerita berikut ini.
Malam itu, sambil menyuapi anaknya makan, Nia (bukan nama sebenarnya) bercerita tentang keadaan yang dialaminya beberapa waktu lalu. Nia (24) merupakan ibu dari seorang anak perempuan yang hampir berusia 1 tahun. Ia juga berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Jayapura. Hari-harinya padat dengan perannya yang berlipat, sebagai seorang ibu dan mahasiswa yang harus menyelesaikan studinya.
“Ini semester akhir, masih ada tugas-tugas praktek.” cerita Nia pendek soal proses kuliahnya.
Nia adalah penyintas KBGO. Perlahan Nia menuturkan kisah tragisnya kala mendapatkan tindakan kekerasan.
Mulanya, Nia mendapat panggilan telepon dan pesan singkat via WhatsApp di suatu malam. Dalam panggilan itu, seorang laki-laki langsung menanyakan tarif dirinya untuk transaksi seksual dalam semalam. Sontak ia kaget dengan rentetan telepon itu. Tidak lama kemudian, temannya menelpon kemudian menyuruhnya mengecek sebuah postingan di akun sosial media X.
Nia membaca cepat sebuah unggahan “Grup Viral Papua 2023” dengan deskripsi singkat “Perempuan lonte suka vcs (video call sex)”. Pemilik akun juga menyebarkan foto, identitasnya, dan caption yang sama di X. Kaget, marah, menangis, kecewa, semua perasaan itu bercampur aduk, bergemuruh di dirinya. Ia melihat sebuah fotonya terpampang jelas di beranda X. Di foto bagian atas adalah wajahnya, namun bagian bawah adalah foto tubuh tanpa busana seorang perempuan.
“Itu bukan sa pu badan, jelas sekali berbeda. Sa tahu sa pu badan seperti apa.” katanya sambil menghela nafas.
Tiba-tiba rasa takut itu kembali menjalar ke seluruh bagian tubuh, kedua kakinya gemetar, peluh di tangannya mulai mengalir.
Di bagian atas postingan di akun X itu, ada keterangan “Silahkan hubungi nomor ini +62 …” Kalimat tidak senonoh dialamatkan ke dirinya mengakhiri postingan itu. Nia lantas menyadari alasan segerombolan laki-laki tiba-tiba mencercanya di telepon.
Kejadian tersebut tepat di bulan Desember 2023. Pelakunya adalah mantan pacarnya. Mereka mengalami Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD), lalu Nia memutuskan melanjutkan kehamilannya sebagai ibu tunggal.
“Kami sudah tidak bersama-sama lagi karena laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab pada kehamilan saya.” katanya.
Pelaku menyebarkan identitas, berupa nama, alamat, nomor telepon, dan foto. Nia menduga ia kemungkinan mengambilnya dari akunnya di media sosial Facebook. Pelaku mencomot dua foto berbeda, lalu mengeditnya menjadi seakan-akan Nia sedang berpose telanjang.
“Foto itu disebarkan seolah-olah itu adalah saya.” tutur Nia.
Ia langsung mengetahui asal muasal foto tersebut melalui sebuah grup yang dikirim menggunakan nomor pelaku.
Setelah kejadian tersebut, nomor pribadinya diserang oleh nomor-nomor tidak dikenal. Mereka meminta untuk melayani Video Call Sex (VCS).
“Nomor saya yang terdaftar di aplikasi Telegram juga langsung ditambahkan dalam grup-grup sex oleh nomor tidak dikenal.” tambahnya dengan nada lirih.
Nia yang ketika itu harus mengurus balita dan perkuliahannya, mengalami situasi terburuk dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia merasa takut melaporkan ke pihak berwajib.
Keluarga Nia, awalnya menunjukkan rasa prihatin namun selama sepekan menunggu kepastian, tidak ada tindakan apapun untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Nia makin terpuruk dan ketakutan, kebingungan mengambil langkah apa yang harus dilakukan sementara ia seorang diri. Nia memilih tidak melapor karena situasinya tengah depresi dan tertekan.
“Ini trauma berat.” ujar Nia.
Dalam hidupnya yang tengah ambang, Nia sempat berteriak histeris kemudian mengiris tangan memakai silet, lalu tidak sadarkan diri. Keluarganya lantas bertindak membawanya ke UGD Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan obat penenang.
Ada lagi sebuah cerita yang sama seperti yang dialami Nia. Berikut kisahnya.
Ayu (45) berkenalan dengan seorang laki-laki di media sosial Facebook. Komunikasi ini berjalan beberapa bulan, keduanya kemudian berpacaran secara online. Mereka belum pernah bertemu, tapi menurut pengakuan laki-laki ini adalah seorang anggota Polisi di luar Papua. Informasi data dirinya cukup jelas dilihat dari profil Facebook, beberapa foto memakai seragam polisi, cukup meyakinkan.
Komunikasi dari Facebook berlanjut hingga ke aplikasi pesan singkat WhatsApp, saling bertukar nomor telepon kemudian mereka berbalas chat hingga video call. Seiring waktu timbul rasa percaya padanya hingga Ayu mulai mengirim foto. Berlanjut laki-laki itu meminta untuk mengirim foto dengan menunjukkan bagian tubuh tanpa busana. Lalu berlanjut hingga menunjukkan organ-organ seksual dan reproduksi saat video call.
Suatu sore, adik perempuannya datang ke rumah. Ayu sedang berbicara di telepon. Di ujung telepon laki-laki itu meminta uang sebesar 10 juta. Selama ini ternyata panggilan dalam video call itu menjadi senjata makan tuan bagi Ayu. Laki-laki itu nyatanya merekam seluruh aktivitas saat video call berlangsung, secara sepihak tanpa kesepakatan Ayu.
Ayu tidak hanya ditipu tetapi juga diancam. Laki-laki itu mengancam akan menyebarkan video-video tersebut. Sontak Ayu kaget dan berteriak histeris ketakutan, ia kemudian mengiba dan memohon.
Adik perempuannya bertanya “Ada apa?”
Ayu gemetar dan pucat, sambil memegang telepon genggam masih berbicara untuk menyakinkan laki-laki itu bahwa uang sebesar itu tidak mungkin didapat dalam waktu satu jam. Namun pelaku bersikukuh akan menyebarkan video-video tersebut jika permintaannya tidak dipenuhi. Adiknya yang ikut mendengar apa yang mereka bicarakan, kemudian menyarankan agar membahas hal ini di luar rumah. Ayu dan adiknya lalu menuju sebuah café yang berada cukup jauh dari rumah.
Ketika sampai di café dan memesan dua gelas teh. Mereka menelpon seorang teman untuk membantu, teman itu menyarankan agar melapor ke Cyber Crime Polda Papua, Tong Pu Ruang Aman, atau LBH APIK Jayapura.
“Saya hanya tahu Cyber Polda, yang lain terdengar asing.” kata Ayu.
Sementara adik Ayu masih gigih baku melawan dengan laki-laki itu. Namun, perlawanan tersebut memicu pelaku nekad bertindak. Pelaku menyebarkan video pendek rekaman layar kepada 10 orang teman terdekat Ayu di Facebook.
“Saya hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Mental saya seperti diadu, meledak, lalu hancur seketika.” tuturnya dengan sedih.
Tidak hanya itu, dia mengirim video ke setiap status (postingan) di kolom komentar. Mengancam lewat tiga nomor WhatsApp berbeda. Mengaku sebagai atasan polisi, juga bekerja di salah satu media dari luar Papua. Pelaku berlagak pintar, mengatakan bahwa ia akan menghubungi temannya, seorang wartawan, lalu mencantumkan peraturan tentang Kode Etik Jurnalistik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai dalih bahwa ancamannya tidak main-main.
Adik Ayu, tidak tinggal diam. Ia dengan cepat membuat sebuah postingan untuk mengklarifikasi bahwa video-video tersebut tersebar bukan atas kemauan Ayu. Terlebih Ayu diancam dan diperas, pelaku meminta uang. Postingan itu mendapat respon yang cukup baik. Kebanyakan yang membalas adalah rekan kerja dan saudara terdekat.
Kedua pihak saling membalas, penuh unggahan caci maki. Adiknya masih bertahan untuk tetap membalas pesan di WhatsApp dan Facebook, menghubungi 10 teman yang menerima postingan itu. Memasang postingan permohonan maaf di Facebook.
Bunyinya, “Saudara saya masih berjuang, saya hanya duduk merasa bersalah.”
Hari sudah malam. Ia lalu menelpon teman yang memberi rekomendasi tadi, tetapi Ayu sempat bimbang, berpikir akan ada biaya melapor.
“Saya tidak ingin melapor karena tidak memiliki uang.”
Temannya meyakinkan, “Tidak perlu membayar, itu gratis.”
“Saya sungguh ingin ini segera selesai. Ini sungguh sebuah kejahatan yang merusak pikiran dan tenaga seharian ini.” ungkap Ayu, meratap.
Walaupun dalam kepanikan dan putus asa, Ayu tetap enggan melapor ke Polisi. Tidak lama postingan-postingan tersebut dihapus. Postingan yang tersebar di Facebook, WhatsApp, dan ancaman telepon menghilang begitu saja. Adik Ayu meyakinkan agar tidak terlalu memikirkan kejadian hari itu.
“Setelah itu, saya tidak berani pulang ke rumah, melihat rumah dari jauh karena masih merasa takut dengan diri ini. Saya trauma tidak membuka lagi aplikasi Facebook.” tutur Ayu mengakhiri ceritanya.
Selain kisah Ayu dan Nia, ada juga kisah Meli. Berikut kisahnya.
Meli (27), pada tahun 2023 ia berkuliah di Jakarta dan aktif dalam gerakan sosial, terlibat sebagai paralegal di Perhimpunan Bantuan Hukum (PBH) Indonesia. Ia kemudian melanjutkan kuliah di sebuah perguruan tinggi di Jayapura tahun 2024. Meli mengaku mendapat edukasi dan informasi soal kekerasan fisik dan online pertama kali dari orang tuanya, juga dari anggota keluarga lainnya.
“Bapa dan Mama memang berikan edukasi tentang penggunaan media sosial, ditambah anggota keluarga lainnya yang ikut memberikan edukasi. Memang saya sadar sekali akan lingkungan sekitar.” ujarnya.
Baginya, jika mendapat ancaman secara online jangan merasa takut untuk melawan. Tenangkan pikiran terlebih dahulu karena jika pikiran kacau selanjutnya kondisi itu membuat bingung, takut, dan cemas. Akhirnya ada rasa khawatir untuk bercerita kepada keluarga atau teman terdekat. Padahal mereka adalah bantuan yang dekat dengan kita.
“Jangan takut cerita kepada orang lain supaya bisa dapat bantuan atau pertolongan.” imbuhnya.
Dunia maya itu kontras dari dunia nyata. Dunia nyata bisa menjadi racun, apalagi dunia maya. Hal baik dan buruk terjadi lewat kecanggihan teknologi. Banyak hal bisa dilakukan dengan adanya teknologi internet, misalnya akses informasi dan jejaring media sosial.
Meli pernah mengalami kekerasan di dunia maya bukan hanya sekali. Kejadian pertama terjadi saat masih duduk di bangku SMP di Wamena.
Seingatnya, seorang paman mendapati fotonya dari sebuah akun di media sosial X. Fotonya diambil dari akun media sosial Facebook lalu disebarkan ke X dengan teks singkat “Berapa ribu foto dan video” dari akun @kudanafsu. Pelaku membuat seolah-olah akun itu dimiliki oleh Meli sendiri yang menjual video dan foto porno.
Untung saja pamannya merespon cepat dengan membuat laporan di Polsek Wamena. Namun laporan itu tidak pernah ada kabarnya hingga dia berangkat ke Jakarta untuk kuliah.
“Saat itu polisi tidak terlalu menanggapi laporan yang dibuat. Kami tidak pernah tahu hasilnya seperti apa?” kata Meli.
Ia menduga kasusnya diabaikan karena penegak hukum hanya fokus kepada pengamanan saja.
Kejadian kedua hampir sama, Meli sudah kuliah saat itu. Ia mendapatkan ancaman lewat aplikasi Messenger. Sebuah pesan masuk, mengatakan adanya video yang sedang viral.
“Pelaku chat lewat saya punya kaka perempuan punya akun, bilang kalau saya viral di akun X. Jadi saya bilang viral apa? Coba screen shoot baru kirim.” imbuh Meli, meminta kakak perempuannya untuk mengirim video yang dimaksud.
Secara bertubi-tubi, 8 akun terus meminta nomor WhatsApp. Pacarnya berinisiatif memberikan nomornya. Mereka juga berusaha mendapatkan keterangan nomor telepon dari aplikasi Get Contact, tetapi tidak ditemukan. Meli bersama keluarganya sepakat untuk membuat laporan ke pihak kepolisian di Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia didampingi pamannya yang sebagai kuasa hukumnya. Namun, Meli mengaku penanganannya cukup lama dan ia tidak pernah mendengar kelanjutan dari laporannya.
“Mungkin juga tidak digubris karena saya tidak pernah mengecek lagi.”
***
Kasus KBGO yang dihadapi Meli mirip dengan pengalaman Nia. Foto dirinya tersebar luas. Wajahnya kentara milik Meli, namun tubuh orang lain. Bedanya dari dua kasus yang dilaporkan Meli. Ia tidak memiliki relasi dengan pelaku. Pelakunya adalah orang asing.
Meli mengatakan akibat kasus KBGO saat di bangku SMP di Wamena, ia mengalami trauma. Di usia sekitar 15 tahun, ia harus menerima gambar yang sangat mengganggu. Di satu sisi, Meli ingin memposting sesuatu untuk membela dirinya, tetapi masih merasa takut akan mendapat respon berbeda dari orang-orang di media sosial.
“Banyak pertimbangan saya ingin bebas berekspresi di sosial media karena orang-orang seperti itu sangat mengganggu kebebasan dalam bersosial media, padahal ini kan hak saya.” gugatnya.
Pernah, ia mencoba membuat sebuah postingan di cerita Instagram supaya teman-teman perempuan berhati-hati. Meli mengunggah foto wajah dirinya yang disebar, tapi pada bagian tubuh telanjang disensor. Tak lupa, Meli mencantumkan cerita kasus yang ia alami. Berbagai komentar masuk, sebagian mendukung namun banyak yang tidak mendukung.
“Apakah ko tidak malu hal-hal seperti ini ditampilkan di media sosial?” komentar seorang kawan di Facebook.
“Saya merasa kita tidak perlu takut speak up di kita punya sosial media. Hal-hal itu (dilakukan) untuk saling mengingatkan kalau saya juga mengalami hal ini. Jangan malu dan takut. Itu masalah yang harus diselesaikan.” tutup Meli.
Pitra Hutomo, relawan TaskForce Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) mengatakan teknologi dibuat untuk memudahkan kehidupan dalam banyak aspek. Sayangnya, teknologi menjadi salah satu alat yang memfasilitasi kekerasan—termasuk KBGO.
KBGO terjadi di media sosial karena ada interaksi minimal dua pihak. Dalam berbagai postingan di media sosial kita dapat melihat konteks aman atau tidaknya seseorang adalah jika ia diserang atau tidak.
Pada dasarnya sebuah serangan tidak bisa diprediksi sehingga konsep keamanan di media sosial jelas adalah bukan ruang yang aman, tetapi bukan serta merta menjadi ruang yang harus dihindari. Meskipun bukan ruang yang aman, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan.
Dari jenis interaksi, misalnya pertimbangan ini gugur jika terjadi kekerasan verbal dari foto dan video apabila pengelola media sosial sudah punya cara-cara untuk mengatasi serangan. Pengguna yang menggunakan media sosial seharusnya mempunyai akses untuk mengetahui seberapa jauh data-data yang ia berikan digunakan, lalu bagaimana dengan perlindungannya, apalagi jika terjadi penyerangan.
Sebuah postingan dengan sangat mudah diubah, artinya masalah perilaku pengguna. Apabila literasi kita sudah maju, perilaku yang merugikan orang lain dalam ranah online tidak akan terjadi. Bahkan, ada beberapa situasi yang disengaja. Pelaku bertujuan untuk mengganggu maupun mengintimidasi usia remaja dan anak kecil, sehingga mereka sebenarnya layak dipenjarakan.
Dimensi Kerentanan KBGO
Remaja atau seseorang di bawah usia 12 tahun memutuskan untuk memiliki akun di media sosial seharusnya menjadi perhatian lingkungannya. Persoalan ini menempatkan siapa saja dalam kelompok rentan, yang sifatnya menuju pada kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun keberagaman gender dan seksual.
“Itu adalah kelompok pertama yang kami identifikasi, juga kelompok dengan identitas gender yang tidak dianggap sesuai dengan norma di Indonesia.” tutur Pitra menjelaskan definisi kelompok rentan mengalami KBGO.
Situasi rentan datang dari realita masyarakat yang memandang laki-laki menempati posisi superior, sementara tubuh perempuan sebagai obyek. Ruang ini tidak jauh beda dengan ruang fisik. Di negara yang lebih moderat keberagaman identitas gender sistem pengaman sosialnya lebih bekerja. Di Indonesia, kelompok rentan pertama selain identitasnya adalah orang-orang yang bisa menggunakan ruang media sosial untuk berlatih berdemokrasi.
“Jadi membicarakan hal-hal yang dianggap terlalu politis, juga rentan, jurnalis juga rentan, karena ruang sosial kita cenderung mengidentifikasi orang langsung. Tipis batasannya antara melakukan KBGO dengan ruang gosip kita.” lanjut Pitra.
Viral Berpotensi Ancaman
Orang menjadi viral atau populer merupakan efek eksistensi di media sosial. Banyak hal sangat mungkin untuk menaikkan popularitas, misalnya konten makan menggunakan sumpit, video ciuman di kebun, dan lain sebagainya.
Selain itu, ada beberapa kondisi yang menjadi sebuah ancaman untuk diviralkan, sebagai contoh video dari seorang transpuan. Reaksi warganet terhadap konten yang berisi atau dikelola oleh transpuan justru sering berisi serangan, ancaman, dan cemooh.
“Kita tidak bisa melepas identifikasi kerentanan dari berbagai hal yang menyusun kehidupan seseorang. Kembali pada kehidupan fisik bagaimana dalam bermasyarakat memperlakukan perempuan, anak, maupun kelompok keberagaman gender dan seksual.” kata Pitra.
Situasi yang terjadi di kehidupan fisik, kalau teridentifikasi secara online bisa mempengaruhi reputasinya. Dampaknya bukan hanya menghancurkan kehidupan dan karakter penyintas, bahkan bisa berujung kematian.
Klasifikasi KBGO
Pengaduan yang masuk di layanan TaskForce KBGO akan diidentifikasi sesuai usia, kerentanan, dan lingkar pendukung.
“Di bawah 18 tahun jika orang tua atau guru tidak mengetahui hal ini, menurut kami adalah kelompok paling rentan.” ujar Pitra.
Jenis aduan KBGO yang masuk di TaskForce di tahun 2022-2023 banyak berkaitan dengan game online. Secara umum, TaskForce KBGO mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan, di antaranya ancaman penyebaran foto, video, dan materi lain, ancaman penyebaran data pribadi (doxing), penguntitan (stalking dan surveillance), pemaksaan atau koersi, membuat foto video (sextortion), ancaman penyebaran identitas gender dan seksualitas (outing), penyebaran data pribadi (extortion), pembuatan akun atas nama korban (impersonasi), kekerasan verbal, hingga kekerasan seksual.
Minimnya Ruang Aman dan Pendidikan Seksualitas
Pitra menilai kerentanan KBGO ini ditambah dengan kurangnya literasi. Bukan pada platform teknologi, tapi berkaitan dengan konsep bisa mendapatkan ruang aman untuk seseorang belajar. Banyak keluarga penyintas ingin masalah cepat selesai dan melakukan rehabilitasi.
“Kalau sikap antipati (penolakan) kami belum ketemu langsung. Kami masuk untuk menjembatani jika ada anak yang takut membicarakan dengan orang tua,” ungkap Pitra.
“Jadi di situ dibikin tim terus ada forum chat private message untuk saling kontak. Untuk pornografi anak ini menjadi hal yang sangat sulit kami telusuri. Melelahkan sekali untuk mengetahui siapa yang ikut mencari dan merepost postingan.” imbuh Pitra lagi.
Menelusuri dan mengusut KBGO berupa foto atau video pornografi seringkali berujung buntu. Jika pelaku hanya tunggal, Pitra mengatakan, proses secara hukum akan lebih mudah. Akan tetapi dunia maya nyaris tak bisa dikontrol, siapa pun bisa mengklik tombol bagikan ulang, sehingga jumlah pelaku bisa berlipat. Kasus yang dianggap layak dan dilanjutkan ke tahap penyelidikan di Indonesia sangat lemah karena penegak hukumnya tidak berjalan.
“(Mengukur) tingkat kesuksesan masalah yang di proses di kepolisian juga rendah. Jika bukan dari kalangan artis atau tokoh tidak sampai 30 persen atau lebih rendah dari itu.” imbuh Pitra.
Cara lain untuk mengusut kasus penyebaran foto maupun video, yaitu lewat mediasi dengan pengacara yang menghubungkan pihak orang tua dan pelaku, syaratnya jika pelaku hanya satu. Penegak hukum harus serius bukan menumpuk aduan, kemudian membuat angka statistik.
Dalam kasus pemaksaan atau koersi, penyintas terkadang tidak menyadari situasinya penuh paksaan dan tekanan.
“(Ada kasus yang dialami seseorang) Belum 10 tahun usianya, belum punya pengetahuan tentang konsep menjalin relasi secara online. Interaksinya tidak melalui hubungan fisik jadi remaja (penyintas) berpikir situasi itu mereka sudah aman.” imbuh Pitra.
Selain itu, kasus pemaksaan terbentuk karena konteks sosial, misalnya bagaimana seseorang berinteraksi dengan laki-laki dan bagaimana relasi kuasa beririsan dengan lingkungannya. Bahkan, kasus pemaksaan atau koersi dapat berlangsung melibatkan orang tua yang melarang anaknya berpacaran.
Di luar dimensi kekerasan seksual, terdapat kasus KBGO yang kerap muncul, yakni doxing (penyebaran identitas seseorang) dan outing (penyebaran identitas gender dan orientasi seksual seseorang).
“Di X sebelum 2010 sudah banyak. Tindakan (doxing dan outing) menyerang teman-teman LGBTQ. Mereka jadi tidak aman, di media sosial X juga mengubah banyak hal.” kata Pitra.
Dunia maya mengizinkan banyak hal, tetapi setiap kebebasan ada resikonya. Perkembangan Artifical Intelegencen (AI) beresiko lebih jauh karena dapat melanggar hak-hak pengguna internet dengan mereplikasi dan memanipulasi foto maupun video. Pitra menekankan, bahwa prioritasnya adalah memastikan bahwa semua orang mau mengadukan dan menindaklanjuti laporan.
Lebih lanjut, Pitra berharap, kita dapat berpikir kritis terhadap Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama persoalan KBGO untuk memberikan keadilan bagi penyintas pengguna media sosial yang rentan, mencakup perempuan, anak, dan kelompok keberagaman gender dan seksual.
“(Kuncinya) Jangan ikut memviralkan.” Tandasnya.
KBGO di Papua
Terlepas dari ketiga pengalaman dari Nia, Ayu, dan Meli, ketika mengalami KBGO, Gilbert Rumboirusi dari Tong Pu Ruang Aman (TPRA) menyatakan bahwa KBGO merupakan salah satu dari tiga kasus terbanyak yang terjadi di Papua. Kasus yang paling banyak ditangani TPRA adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), dan Kekerasan Gender Online (KBGO). Sejak April hingga 31 Desember 2023 terdapat 446 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan dari masa sebelumnya.
“Sebanyak 229 kasus dialami atau melibatkan Orang Asli Papua (OAP). Jadi kurang lebih sedikit sebanyak 54 persen.” ujar Gilbert.
Gilbert menjelaskan setelah mendapatkan pengaduan, TPRA melakukan penilaian (assessment) awal untuk memastikan rating dari kasus tersebut, apakah butuh penanganan segera atau perlu menggali informasi lebih dalam lagi.
“Setelah itu kita lihat apa yang dibutuhkan oleh penyintas. Kalau belum melakukan visum, kami akan minta agar korban segera divisum. Setelah itu kita tentukan skema rapat untuk menentukan skema advokasi apa yang akan kita kerjakan. Kemudian kasusnya kami dampingi setelah mengetahui skema advokasi seperti apa yang akan kita kerjakan.” lanjut Gilbert.
Proses pendampingan tergolong menjadi dua, beberapa kasus bisa melalui layanan konsultasi, sementara lainnya butuh pendampingan langsung. Dari jumlah 446 kasus yang ditangani, hanya sekitar 96 kasus yang dapat diselesaikan hingga tuntas. TPRA mengalami kendala karena klien seringkali tidak ingin melanjutkan kasus atau proses hukum yang berjalan di tempat.
“Kami hanya memberikan untuk advice (saran) hukum secara online untuk beberapa kasus di luar kota. Jadi kami belum bisa memastikan sudah sejauh mana penyelesaiannya.” ujar Gilbert.
Tantangan yang dihadapi lainnya adalah kondisi aparat penegak hukum yang tidak responsif, minim perspektif gender, dan nir keberpihakan kepada penyintas. Berhadapan dengan masyarakat umum, penyintas kurang mendapat dukungan. Hal ini berpotensi terulang jika melapor ke aparat hukum. Dalam situasi kasus KBGO, kinerja aparat pada Unit Cyber Polda Papua terbilang masih sangat lambat.
Gilbert mengungkapkan TPRA memberi dukungan kepada penyintas karena aparat yang terkesan tidak terlalu serius dalam menangani pelaporan maupun pengaduan. Salah satu cara yang ditempuh ketika menangani kasus KBGO adalah dengan membuat puluhan akun media sosial untuk membantu melaporkan postingan yang menyerang korban.
“Ada beberapa klien kami yang merasa terbantu dengan apa yang kami lakukan ketimbang melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum, namun tidak ada kejelasan.” tutup Gilbert pendek.
Melapor untuk KBGO
Apabila kalian mengalami kasus kekerasan berbasis gender dan seksual, baik secara langsung maupun terjadi di ranah online dan membutuhkan bantuan silahkan hubungi: Pertama: Tong Pu Ruang Aman, lewat layanan telepon 0821-9862-8327 maupun akun Instagram @tong_pu_ruang_aman, kedua: TaskForce KBGO, masuk lewat formulir aduan http://tinyurl.com/mengalamikbgo. Kedua layanan ini dapat diakses gratis.
***
Catatan: Isi dari artikel ini dapat memicu trauma dan menimbulkan ketidaknyamanan, khususnya bagi para penyintas depresi, percobaan bunuh diri, kekerasan berbasis gender online, kekerasan seksual, maupun kekerasan dalam berpacaran. Tulisan ini merupakan karya dari partisipan workshop menulis untuk perayaan International Women’s Day (Hari Perempuan Sedunia) 2024 bertema “Inspire Inclusion: Ambil, Rebut, Ciptakan, dan Pertahankan Ruang untuk Perempuan di Tanah Papua” yang didukung oleh Lao-Lao Papua, Elsham Papua, Yayasan iWaTaLi Papua, Parapara Buku, dan Yayasan Pusaka.